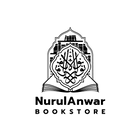Mengenal Sifat Diri Insān, Bagaimana Ia Mempengaruhi Klasifikasi Manusia Dan Cara Mengurus Tadbir Mereka
Oleh Zainul Abidin bin Abdul Halim
Insān ini walaupun sama pada asas sifat keinsanannya, namun ternyata kadar keinsanannya itu berbeza-beza; ada yang sempurna keinsanannya, ada yang kurang. Yang saya maksudkan dengan sifat keinsanan ini adalah ciri asas yang membezakan bangsa insan daripada bangsa-bangsa makhluk yang lain.
Ahli falsafah dan manṭiq menta‘rīfkan insān sebagai “al-ḥayawān al-nāṭiq” yang jika diterjemahkan secara literal bererti “haiwan yang bercakap”. Jika inilah kefahaman yang dikehendaki oleh golongan yang punya akal yang kuat itu, sudah pasti burung kakak tua yang diajar bercakap juga termasuk dalam kalangan insān. Hal ini tidak dapat diterima oleh manusia yang memiliki ‘aqal yang sihat, apatah lagi pemikir-pemikir yang mempunyai ‘aqal yang subur dan kuat.
Ma‘nā “al-ḥayawāniyyah” (sifat kehaiwanan) di sini -jika diteliti secara lebih mendalam- bererti “suatu jisim yang boleh tumbuh berkembang dan membesar serta mampu bergerak sesuai kehendaknya sendiri”. Difahami daripada ta‘rīfan ini bahawa ada dua komponen yang membina hakikat “al-ḥayawāniyyah”. Pertama: jisim yang mampu tumbuh membesar dan berkembang. Ciri ini membezakannya daripada batu-batuan serta objek-objek yang tidak bernyawa. Yang tersisa dalam ruang lingkup “al-ḥayawāniyyah” hanyalah tumbuh-tumbuhan dan hidupan. Namun, apabila kita meneliti ciri yang kedua pula; iaitu yang mampu bergerak sesuai kehendaknya sendiri, kita mendapati tumbuhan juga akhirnya tidak dapat naik ke darjat “al-ḥayawāniyyah”. Yang tersisa di dalam daerah ḥayawān kini hanya hidupan.
Pada ketika ini, kita berhadapan dengan satu persoalan: “Adakah semua hidupan berada pada martabat yang sama? Atau ada perbezaan martabat antara satu hidupan dengan hidupan yang lain?” ‘Aqal fikiran kita tidak menganggap mustahil kewujudan pelbagai martabat dalam susunan jisim-jisim itu tadi (bermula daripada jisim yang kaku seperti batu sehinggalah kepada jisim yang hidup). Oleh itu, boleh jadi ada juga martabat-martabat yang pelbagai bagi jenis-jenis hidupan yang berbeza-beza ini.
Demi memastikan kedudukan sebenar martabat insān di antara pelbagai jenis hidupan, ‘aqal perlu mencari apakah ada ciri yang menjadikan bangsa ini berbeza daripada bangsa-bangsa hidupan yang lain? Bahkan adakah ciri yang membezakan mereka ini merupakan suatu keistimewaan yang dapat mengangkat darjat mereka ke martabat yang lain yang lebih tinggi berbanding hidupan yang lain? Pengembaraan ‘aqal dalam diri insān ini akhirnya mengembalikannya kepada dirinya sendiri; iaitu ‘aqal itu sendiri. Ternyata nilai diri jisim yang boleh bergerak dengan sendirinya ini terletak pada ‘aqalnya; iaitu kemampuannya memahami hakikat-hakikat perkara. Lalu, kefahamannya terhadap hakikat-hakikat ini diungkapkan dengan lidahnya yang fasih berbahasa dan berkata-kata. Inilah ma‘nā ciri kedua yang terdapat dalam ta‘rīfan diri insān tersebut; iaitu ma‘nā “al-nāṭiqiyyah”.
Namun, “al-nāṭiqiyyah” yang merupakan keistimewaan diri insān ini, tidak hanya menyentuh aspek pemikiran dan kefahamannya sahaja, ia juga menuntut agar insān ini akur dan mentaati hakikat-hakikat yang dikecapi oleh ‘aqal. Pengakuran dan ketaatannya ini hanya terbukti apabila kesemua duduk-gerak dan kerja-buat insān tersebut terbit daripada kehendaknya yang didasari oleh kefahaman ‘aqalnya terhadap hakikat-hakikat sebenar semua perkara.
‘Aqal dan Kehendak Insān
Apabila kehendaknya (yang terpancar pada gerak tubuh badan dan perbuatannya) dan ‘aqalnya sama-sama akur terhadap hakikat kebenaran dan sama-sama mengingkari kebatilan, maka ‘aqal yang mewakili aspek bāṭin dan spiritual diri insan itu telah menyatu dengan aspek ẓāhir dan fizikalnya. Tubuh badannya yang merupakan tempat akhir penzahiran bagi apa yang ada di alam ‘aqalnya telah menjadi saksi kebenaran ‘aqal yang menjadi sumber pertama gerak tubuhnya ke arah hakikat dan ke arah kebenaran. Insān ini telah merasa secebis ma‘na “dia yang pertama dan dia yang terakhir, dia yang ẓāhir dan dia yang bāṭin.”
Kehendak yang berlandaskan kebenaran yang dikecapi oleh ‘aqal, inilah kesempurnaan ma‘nā al-ḥayawāniyyah. Manakala kata-kata yang terbit daripada hakikat-hakikat kebenaran yang dipetik oleh ‘aqal pula merupakan kesempurnaan ma‘nā al-nāṭiqiyyah.
Oleh itu, burung kakak tua tidak lagi termasuk dalam kategori insān kerana kata-katanya tidak bersumber dari ‘aqal sama sekali. Bahkan, manusia yang bercakap sesuai kehendak nafsu syahwat dan kemarahannya, tidak berlandaskan ‘aqalnya, juga tidak memiliki kesempurnaan ma‘nā al-nāṭiqiyyah. Bahkan jika seseorang berkata sesuai tuntutan ‘aqalnya sekalipun, namun ‘aqalnya masih belum sempurna memahami hakikat-hakikat perkara, maka orang ini juga belum mencapai kesempurnaan ma‘nā al-nāṭiqiyyah.
Kehendak yang berlandaskan kebenaran yang dikecapi oleh ‘aqal adalah kehendak istimewa yang membezakan insān daripada haiwan. Kehendak haiwan hanyalah didasari nafsu dan kemarahan. Ia bergerak mengejar mangsa dan mendekati haiwan betina kerana nafsunya, ia membunuh musuhnya kerana sifat marah yang melahirkan keberanian dalam dirinya. Tetapi ia tidak mampu menahan nafsu atau kemarahannya demi kebaikan yang lebih besar yang hanya difahami melalui jalan ‘aqal. Kerana itulah kehendak haiwan tidak sempurna seperti kehendak insān. Jika insān membiarkan nafsu dan kemarahan mengemudi diri dan perlakuannya, maka dia telah turun ke darjat haiwan. Bahkan lebih hina daripada haiwan; kerana bangsa haiwan berkehendak sesuai capaian tertinggi dirinya iaitu nafsu dan kemarahannya, sedangkan manusia ini meninggalkan nikmat kurniaan tertinggi iaitu ‘aqalnya, dia mensia-siakannya dan tidak menggunakannya untuk membentuk akhlak dan perlakuannya.
Dengan ini, jelaslah bagi insān akan kedudukan dan martabatnya berbanding bangsa-bangsa yang lain. Penelitian ‘aqalnya terhadap alam dan bangsa-bangsa yang mendiami alam ini menatijahkan bahawa dialah yang berada di tempat tertinggi susunan martabat penduduk bumi ini. Kewujudan susun atur martabat ini juga ditunjukkan oleh wahyu apabila menceritakan peringkat-peringkat dan martabat syurga dan neraka serta darjat-darjat malaikat. Kesemuanya menunjukkan bahawa sistem kewujudan ini terbina di atas satu asas yang sama; asas tertib dan susunan peringkat bermartabat. Hal yang sama juga telah dinyatakan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-‘Aṭṭās di dalam sebahagian karya agungnya.[1]
Setelah pengembaraan jauh ‘aqal di dalam alam jasmani dan rūḥānī, ‘aqal akhirnya mengenal dirinya sendiri. Ketika ini dia mengerti benar bahawa dirinyalah yang paling layak mentadbir kerajaan diri insān kerana kemampuannya memahami dan mengakui hakikat-hakikat dan kebenaran sesuatu perkara. Dalam masa yang sama ‘aqal juga memahami bahawa sejauh mana usahanya memahami rahsia dirinya, dia tetap tidak mampu menyingkap rahsia dirinya ini. Bahkan untuk memberikan ta‘rifan dan ma‘nā bagi kalimah (‘aqal) itu sendiri, tidak mampu untuk ‘aqal lakukannya. Jadi bagaimana dia mampu mengecapi hakikat yang lebih besar dan agung; iaitu hakikat penciptanya. Kata-kata sebahagian ulama mula menerpa ke dataran ‘aqal. Kata-kata tersebut berbunyi:
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ
Ma‘nā zahir kata-kata ini “barangsiapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya”. Namun ‘aqal insan sendiri tidak terdaya memahami ma‘nā ‘aqal, ma‘nā jiwa dan ma‘nā rūḥ yang membentuk hakikat diri insān, maka bagaimanakah dia mampu mengenal hakikat Penciptanya Yang Maha Agung? Apabila diteliti secara lebih mendalam, ternyata kata-kata ini juga dapat difahami dengan ma‘nā yang menunjukkan bahawa ‘aqal adalah tuan yang berhak memiliki dan mentadbir diri insān tersebut. Ini dapat difahami jika lafaz “rabb” di dalam kata-kata itu difahami secara literal yang bererti: tuan, pemilik atau yang berhak ke atas sesuatu perkara. Ganti nama (ḍamīr) yang berada setelah lafaz “rabb” ini pula merujuk kepada lafaz “nafs” yang bererti diri insān. Seolah-olah kata-kata ini memberi erti: “Barangsiapa yang mengenal (iaitu meneliti dan memahami) dirinya, maka dia akan mengenal tuan (iaitu raja yang memiliki dan mentadbir) dirinya.”
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ مَالِكَ نَفْسِهِ
Tidak syak lagi raja tersebut adalah ‘aqal fikirannya, bukan nafsu syahwat dan kemarahannya. Saya kira hal ini tidak perlu dihuraikan secara lebih mendalam lagi di kesempatan ini, kerana hal yang menjadi keutamaan kita di dalam penulisan ini adalah mengenal aspek-aspek yang membentuk hakikat insān itu sendiri dan bagaimana aspek-aspek ini mempengaruhi pembahagian kategori insān.
Klasifikasi Manusia dan Cara Mengurus Tadbir Mereka
Telah dinyatakan di atas bahawa kesempurnaan insān terletak pada kesempurnaan nāṭiqiyyah dan ḥayawāniyyahnya, atau dengan bahasa yang lebih mudah, kesempurnaannya terletak pada kesempurnaan ‘aqalnya untuk memahami kebenaran dan kesempurnaan kehendaknya untuk mencari dan menuju kepada kebenaran atau melakukan sesuatu perbuatan sesuai kebenaran yang telah dicapai oleh ‘aqalnya. Hal ini -jika difahami dengan baik- akan membawa kita merenung bangsa manusia dan mengakui bahawa tidak semua manusia mampu memahami hakikat-hakikat perkara dan tidak semua manusia mampu bertindak sesuai kefahaman hakikat sesuatu perkara. Kenyataan atau realiti ini menyebabkan terwujudnya beberapa kelompok atau kategori manusia. Setiap kategori ini memerlukan cara yang berbeza-beza untuk diurustadbir dan dipimpin ke arah kebenaran.
Imam al-Ghazālī telah menghuraikan kategori manusia dan cara memimpin mereka menuju kebenaran dengan amat baik sekali.[2] Secara umumnya, dapat dikatakan bahawa terdapat 3 golongan manusia. Pertama: golongan yang bagus ‘aqal dan betul kehendaknya (intention). Kedua: golongan yang tidak bagus ‘aqalnya dan tidak ada kehendaknya. Ketiga: golongan yang lahir dicelah kedua-dua golongan itu tadi.
Golongan Pertama Manusia dan Cara Membimbing Mereka
Golongan pertama ini juga dikenali sebagai golongan khawāṣ (golongan khusus). Mereka mempunyai tiga ciri yang membezakan mereka daripada golongan yang lain. Pertama: kuat ‘aqal fikiran sehingga memungkinkan mereka untuk memahami hakikat-hakikat perkara. Hal ini tidak dapat diusahakan oleh seseorang, sebaliknya ia adalah pemberian Allah Taala. Kedua: suci jiwa mereka daripada belenggu taqlīd dan taksub mazhab. Ciri ini menggambarkan kehendak jiwanya yang hanya inginkan kebenaran tanpa terikat dengan nama-nama tokoh tertentu atau mazhab tertentu. Ciri yang pertama dan kedua ini menzahirkan kesempurnaan ‘aqal dan kehendak orang itu. Namun, untuk membolehkan kecerdikannya dan kehendaknya yang baik itu digunakan untuk memahami hakikat perkara dan mencapai kebenaran, serta membolehkannya mentadbir urusan diri dan masyarakatnya pula, dia perlu dilengkapi dengan asas-asas berfikir yang betul.
Asas berfikir yang betul ini adalah bentuk-bentuk qiyas manṭiqī yang dikeluarkan kaedah-kaedahnya daripada al-Qur’ān. Ia merupakan kaedah berfikir para Nabi A.S. yang tidak memiliki kecacatan dan kesalahan dalam penyusunan bukti-bukti dan natijahnya. Seseorang yang memahami timbangan ‘aqal ini bukan hanya dapat memahami hal urusan agama sahaja. Dia juga akan dapat memahami ilmu matematik, kejuruteraan, perubatan, fiqh, ilmu Kalām dan semua bentuk ilmu yang hakiki, bukan ilmu yang direka-reka.[3] Ilmu berfikir inilah yang disebut sebagai ḥikmah. Sesiapa yang dikurniakan ḥikmah maka dia telah dikurniakan kebaikan yang banyak. Hal ini sukar untuk diperolehi melainkan dengan bantuan guru yang benar. Kerana inilah, dia perlu memiliki ciri yang ketiga yang akan dinyatakan di sini.
Ciri yang ketiga: dia meyakini bahawa guru yang akan memberikannya petunjuk dan kaedah memperoleh kebenaran itu adalah guru yang mempunyai autoriti, kepakaran dan sememangnya tergolong dalam kalangan ulama’ yang mempunyai pandangan mata hati yang tajam dan timbangan ‘aqal yang betul. Imam al-Ghazālī juga mengatakan bahawa orang yang tidak meyakini gurunya pandai matematik dia tidak akan dapat mempelajari ilmu matematik daripada gurunya itu.
Apabila kenyataan ini ditujukan kepada guru saya Dr. Khālid Zahrī al-Maghribi, beliau menjelaskan bahawa perbandingan ilmu logik akal dengan ilmu matematik yang dibuat oleh Imam al-Ghazālī ini merupakan suatu perbandingan dan perumpamaan yang amat baik. Ini kerana kedua-dua bidang ilmu ini (ilmu logik ‘aqal dan ilmu matematik) merupakan bidang ilmu yang mengandungi bukti kesahihan dan kebenarannya di dalam diri ilmu tersebut tanpa perlu merujuk kepada bukti-bukti luar.
Namun, tetap sahaja seseorang penuntut kebenaran memerlukan guru dan perlu meyakini keilmuan gurunya dalam bidang tersebut; atau dengan erti kata lain dia perlu mengimani ketokohan gurunya dalam bidang tersebut walaupun dia belum memahami ilmu itu. Setelah dia menguasai asas-asas ilmu itu dan mempraktikkannya, barulah dia dapat memastikan kebenaran dan kealiman gurunya, tetapi bukanlah kerana keyakinannya kepada gurunya semata-mata, sebaliknya kerana ilmu matematik atau ilmu logik itu sendiri yang membuktikan kebenaran gurunya dan menatijahkan keyakinannya terhadap gurunya. Imam al-Ghazālī menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahawa “kefahaman hanya diperolehi setelah keimanan.”
Secara tidak langsung, kenyataan ini menunjukkan bahawa walaupun sesuatu kebenaran telah jelas, tetapi kebanyakan manusia perlu diberikan peringatan dan ditunjukkan ke arah kebenaran tersebut. Golongan yang kuat ‘aqalnya seperti golongan pertama ini akan segera memahami dan mengakui kebenaran itu apabila diberikan isyarat ke arahnya. Golongan yang kurang sedikit kekuatan ‘aqalnya pula harus dibimbing dan ditunjuk satu persatu penyelesaian masalah matematik tersebut. Hal ini seperti keadaan golongan kedua yang lebih cerdik daripada kalangan awam, tetapi kecerdikannya tidak sempurna seperti golongan pertama. Apabila golongan ini telah memahami ilmu matematik tersebut maka mereka akan akur dan menerima kebenaran itu jika sememangnya jiwa mereka menghendaki kebenaran. Golongan yang lemah ‘aqalnya pula (iaitu golongan awam) sememangnya tidak mampu memahami penyelesaian masalah tersebut, namun selagi mereka mempercayai kealiman guru tersebut dalam bidang matematik maka mereka akan akur dan mengikut petunjuk guru tersebut. Dengan ini, guru yang rabbānī tersebut mampu mengurus tadbir semua golongan dan menyatupadukan mereka serta memimpin mereka menuju jalan yang benar.
Namun, jika golongan khawāṣ yang dikurniakan ketajaman ‘aqal dan kehendak yang betul ke arah kebenaran tidak sanggup membuka pintu fikirannya untuk duduk dan mendengar kata-kata guru tersebut, sebaliknya dia lebih mengutamakan keraguan dan syak wasangka terhadap apa sahaja yang disampaikan oleh orang lain kepadanya; maka selamanya dia tidak akan dapat mengetahui kaedah-kaedah berfikir yang betul. Atau mungkin dia akan mengetahuinya setelah suatu tempoh renungan dan penelitian ‘aqal yang amat panjang. Sayangnya, usianya ketika itu sudah pasti tidak memungkinkannya untuk menggunakan ilmu tersebut bagi memperbaiki keadaan diri dan masyarakatnya. Inilah tiga syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang yang ingin berada di dalam kategori ahli ḥikmah.
Golongan Kedua Manusia dan Cara Membimbing Mereka
Golongan yang kedua pula adalah golongan awam. Mereka dapat diklasifikasikan kepada beberapa golongan. Pertama: orang yang tidak dikurniakan kekuatan ‘aqal untuk memahami hakikat-hakikat perkara. Kedua: orang yang dikurniakan ‘aqal yang kuat tetapi tiada kehendak untuk memahami hakikat sesuatu perkara kerana dirinya disibukkan dengan hal-hal lain seperti pekerjaan, pertukangan dan kemahiran. Ketiga: orang yang tiada kekuatan ‘aqal namun berkehendak untuk mengetahui hakikat perkara. Ketiga-tiga golongan ini merupakan golongan awam. Ketiadaan kekuatan ‘aqal menyebabkan mereka tidak mampu memahami hakikat yang akan disampaikan walaupun mereka berkeinginan untuk mengetahuinya. Manakala ketiadaan kehendak untuk mencari hakikat-hakikat perkara akan menyebabkan usaha menyampaikan hakikat kepadanya terbantut walau orang tersebut cerdik sekalipun.
Secara umumnya, ketiadaan salah satu daripada aspek ‘aqal yang kuat dan kehendak yang benar atau ketiadaan kedua-duanya sekali akan menyebabkan seseorang berada dalam golongan awam. Jika terbit di dalam jiwanya kehendak mendapatkan hakikat, namun kehendak tersebut tidak lurus dan betul; maka ketika itu dia tergolong dalam golongan yang ketiga yang akan dihuraikan setelah ini.
Kaedah memimpin golongan awam adalah dengan memberikan nasihat dan peringatan atau juga disebut sebagai mau‘iẓah. Golongan awam tidak sepatutnya dibiarkan bergelumang dengan masalah-masalah khilāfiyyah yang akan membinasakan dirinya. Imam al-Ghazālī memberi perumpamaan seorang lelaki yang menghabiskan umurnya menguasai ilmu penulisan dan sastera, dia sudah pasti tidak tahu ilmu menenun kain. Begitu juga orang awam yang menghabiskan umurnya dalam urusan-urusan lain selain ilmu, maka bagaimanakah dia ingin berkecimpung dalam bidang keilmuan? Bahaya ilmu yang membawa kepada khilaf -bagi orang awam- adalah lebih besar daripada bahaya melakukan dosa besar; ini kerana ada sebahagian daripada ilmu-ilmu khilaf yang boleh menyebabkan orang awam jatuh ke dalam kekufuran tanpa dia sedari.

Bagi mengeluarkan orang awam daripada bahaya khilaf ini, mereka mestilah dipandu dengan mau‘iẓah al-Qur’ān; mereka hendaklah mengimani hal-hal ‘aqīdah yang dinyatakan di dalam al-Qur’ān. Jika ada hal yang tidak jelas di dalamnya maka katakanlah: “Kami beriman dengan Allah, semua yang dinyatakan ini adalah daripada-Nya.” Berimanlah dengan kesemua sifat-sifat Allah yang dinyatakan dalam al-Qur’ān dengan disertai penafian keserupaan dengan makhluk.
Dalam hal syariat pula, mereka hendaklah memahami dan menguasai kesemua hal yang disepakati oleh semua ulama’ terlebih dahulu sebelum masuk ke perbahasan yang tidak disepakati dan berlaku khilaf padanya. Ini kerana hal yang disepakati tersebut merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh semua manusia tidak kira dia memiliki ‘aqal yang kuat atau tidak. Jika orang awam berusaha memahami hal-hal khilaf syariat sedangkan dia belum menguasai hal yang wajib dan disepakati, maka keadaannya samalah seperti orang sakit yang hampir membinasakan dirinya, dihadapannya ada ubat yang mujarab disepakati oleh semua para doktor keberkesanannya, namun dia tidak mengambil dan memakan ubat tersebut, sebaliknya dia berkata: “Para doktor berbeza pendapat mengenai sejenis ubat sama ada ubat tersebut memberi kesan panas atau sejuk terhadap tubuh badan. Boleh jadi suatu hari nanti saya memerlukan ubat tersebut. Oleh itu, saya tidak akan merawat diri saya dengan ubat yang disepakati ini selagi mana saya tidak mengetahui hakikat ubat itu tadi yang mungkin saya akan gunakan suatu hari nanti.” Jika beginilah keadaan orang awam itu, maka bukan hanya tubuh badannya yang sakit, tetapi ‘aqalnya juga sakit dan hampir binasa. Inilah golongan yang kedua dan cara merawat mereka adalah dengan mau‘iẓah.
Golongan Ketiga Manusia dan Cara Membimbing Mereka
Golongan yang ketiga pula adalah yang lahir di antara dua golongan itu tadi. Mereka adalah golongan ahli debat (jadal). Golongan ini terbahagi kepada dua. Pertama: golongan yang lebih cerdik berbanding golongan awam, tetapi tidak sampai ke darjat ahli ḥikmah. Kedua: golongan yang dikurniakan kecerdikan, namun kehendaknya kepada kebenaran dikotori dengan taksub, taqlid dan pengingkaran yang akhirnya membinasakan dirinya.
Kaedah merawat dan menuntun mereka ke arah kebenaran adalah dengan cara berlemah lembut dengan mereka dan tidak memarahi mereka serta berdebat dengan hujah yang terbaik. Cara berhujah yang terbaik ini adalah dengan menjadikan titik-titik persamaan dan kenyataan-kenyataan yang diterima oleh kedua-dua belah pihak sebagai asas penghujahan yang akan menatijahkan kebenaran pendapat yang ingin disampaikan kepada mereka.
Setelah itu, kecerdikan yang ada pada diri ahli debat itu sendiri yang akan memimpinnya memahami kebenaran hakikat yang ingin disampaikan kepadanya. Sifat inginkan kebenaran pula akan membantunya mengakui dan akur terhadap kebenaran tersebut.
Inilah tiga kaedah mengurustadbir manusia; ḥikmah bagi golongan khawāṣ, mau‘iẓah bagi golongan awam, dan jidāl atau perdebatan yang baik bagi golongan pertengahan. Pembahagian cara menguruskan manusia ini sebenarnya berasal dari sumber waḥyu. Allah berfirman:
ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل: 125)
“Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalan-Nya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.”
Ada ketikanya ahli jadal ini tidak dapat mengakui dan menerima kebenaran. Hal ini boleh jadi sedemikian kerana dia menginginkan hujah dan penerangan yang lebih lanjut. Jika begitu keadaannya, maka bolehlah diajar kaedah-kaedah berfikir seperti yang diajarkan kepada ahli ḥikmah itu tadi. Namun, jika dia tetap berkeras tidak ingin menerima dan akur dengan hakikat dan kebenaran yang disampaikan kepadanya -setelah diajar kepadanya ilmu ahli ḥikmah- maka kedegilannya ini tidak lain tidak bukan adalah kerana ketidaksempurnaan ‘aqalnya; iaitu dengan bahasa yang lebih kasar, kerana kebodohannya, atau kerana kehendaknya untuk memperolehi kebenaran tidak betul. Kehendaknya tidak bersumberkan cahaya ‘aqalnya, sebaliknya kehendaknya itu bersumberkan nafsunya untuk memenangkan pendapat dan ikutannya.
Ketika ini, dia hanya dapat dirawat dengan besi; iaitu dengan cara pihak berkuasa menghukum atau memenjarakannya. Kerana inilah Allah mengutuskan bersama-sama para Anbiyā’: al-Ḥadīd, al-Kitāb dan al-Mīzān. Al-Kitāb iaitu kitab sumber perundangan-Nya bagi meluruskan ahli mau‘iẓah, al-Mīzān iaitu timbangan ‘aqal bagi meluruskan ahli ḥikmah, dan al-Ḥadīd iaitu besi pula bagi meluruskan ahli debat yang mengingkari kebenaran. Allah berfirman:
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (الحديد: 25)
“Demi sesungguhnya! Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan Kami telah menurunkan bersama-sama mereka Kitab Suci dan neraca keadilan supaya manusia dapat menjalankan keadilan, dan kami telah menciptakan yang mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah bagi manusia.”
Allah Taala mencegah sesuatu keburukan yang tak tercegah dengan al-Qur’ān melalui jalan kekuasaan (kerajaan). Inilah cara merawat golongan yang sentiasa hidup dalam pengingkaran terhadap kebenaran.
Dengan ini, jelaslah bahawa bangsa insān sememangnya mempunyai kategori dan klasifikasi yang berbeza-beza. Cara mendidik dan meluruskan mereka juga berbeza-beza kerana cara tersebut berkait rapat dengan sifat atau aspek dalaman diri mereka; atau dengan erti kata lain, ia berkait rapat dengan kualiti aspek nāṭiqiyyah yang terzahir pada ‘aqal dan kualiti aspek ḥayawāniyyah yang terzahir pada kehendak diri. Oleh itu, kita tidak sepatutnya mengajar orang awam ilmu ḥikmah kerana mereka sememangnya tidak akan mampu menggarap hal tersebut, seperti mana kita tidak boleh memaksa ahli ḥikmah yang tajam ‘aqal dan kuat pandangan hatinya untuk menerima pendapat atau kata-kata seseorang hanya dengan semata-mata karāmah atau hal yang menakjubkan yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa mereka mengetahui bukti-bukti kebenaran kata-katanya berdasarkan hujah ‘aqal. Begitu juga kita tidak boleh mengeluarkan semangat atau rūḥ perdebatan yang ada di dalam jiwa ahli debat. Sebaliknya mereka semua mestilah dididik dengan perkara yang menepati sifat fiṭrah mereka.
Rajah Kategori Manusia Berdasarkan Kualiti Sifat ‘Aqal Dan Kehendak
Penulis mendapat pendidikan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam di Universiti Qadhi Iyyadh, Marrakech, Maghribi. Setelah itu melanjutkan pengajian Ijazah Sarjana di Fakulti Usuluddin Universiti Abdul Malik Saadi, Tetouan, Maghribi dalam bidang Usuluddin dan Syariah di Barat Dunia Islam. Mempunyai beberapa penulisan dan kajian antaranya ialah Sejarah Ringkas Mazhab Asy'ari di Maghribi, dicetak oleh Nizamiyyah Institute, Kuala Lumpur.
Nota
[1] Lihat tajuk “The Degrees of Existence” dalam: Syed Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena to The Metaphysics of Islam (Kuala Lumpur, ISTAC, 1995), ms/267 dan setelahnya.
[2] Lihat lebih lanjut perbahasan ini pada bab “Pada Membicarakan Mengenai Jalan Keluar Daripada Kegelapan Perselisihan Bagi Manusia” dalam: al-Ghazālī, Timbangan Yang Adil, terj. Abdullah Zawawi (Kuala Lumpur: Nizamiyyah Publications & Distributors, 2021M).
[3] Al-Ghazālī, al-Qisṭās al-Mustaqīm (Jeddah: Dar al-Minhāj, 2016M), 121.